Bahaya psikologis curhat ke AI sempat menjadi bahan diskusi hangat di media sosial. Salah satu contohnya datang dari kisah seorang wanita bernama Kendra yang kerap mencurahkan isi hati kepada ChatGPT, bahkan sampai menamainya Henry. Cerita ini kemudian dibahas oleh akun TikTok @hansoljang110, yang memang dikenal sering mengangkat fenomena sosial dengan gaya bercerita yang ringan dan mudah dipahami.
Fenomena Kendra dan “Henry†ini membuka mata banyak orang tentang kebiasaan baru: menjadikan chatbot sebagai teman curhat. Wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya aman nggak sih kalau kita menuangkan perasaan ke AI layaknya curhat ke sahabat atau bahkan psikiater?
Psikiater Indonesia, Dr. Andri, SpKJ (Psikosomatik RS OMNI Alam Sutera), lewat kanal YouTube-nya mengingatkan bahwa AI bukanlah dokter. Menurutnya, AI memang bisa menyajikan informasi, tapi tidak memiliki pengalaman klinis dan pertimbangan manusiawi yang hanya dimiliki psikolog atau psikiater. Bahkan, menurutnya AI sering salah dalam memaparkan sesuatu, dan seringkali perlu di kroscek ulang.
Senada dengan kekhawatiran tersebut, sebuah tinjauan literatur akademis yang dipublikasikan dalam e-jurnal Universitas Nurul Jadid (UNUJA) juga menyoroti keterbatasan mendasar dari chatbot AI dalam ranah kesehatan mental. Meskipun penelitian ini menemukan bahwa chatbot dapat menjadi alat skrining awal yang efektif untuk mengurangi gejala depresi atau kecemasan, riset tersebut secara tegas mencatat bahwa chatbot tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian klinis yang mendalam.
Selain itu, AI juga kurang memiliki kemampuan berpikir kritis dan berisiko mengalami misdiagnosis dalam kasus yang kompleks. Oleh karena itu, chatbot tidak bisa menjadi pengganti interaksi dengan psikolog atau psikiater yang memiliki empati, pengalaman, dan keahlian untuk memberikan diagnosis dan rencana perawatan yang personal serta aman.
Nah, supaya lebih jelas, mari kita bahas satu per satu apa saja bahaya psikologis curhat ke AI yang perlu kita waspadai.
8 Bahaya Psikologis Curhat Ke Chatbot AI
1. Rasa Nyaman yang Semu

Curhat ke AI memang sepertinya bisa bikin kita merasa lega sejenak, karena ada “seseorang†yang selalu siap merespons. Kata-katanya sopan, jawabannya cepat, bahkan seolah penuh perhatian. Tapi sebenarnya, AI tidak benar-benar paham dengan emosi kita. Ia hanya menyusun kata-kata berdasarkan pola dari data, bukan dari empati yang tulus.
Akibatnya, meskipun terlihat seperti sedang didengarkan, kebutuhan emosional kita sering kali tidak benar-benar terjawab. Yang ada, kita terjebak dalam ilusi seolah dimengerti, padahal rasa kosong di dalam diri masih tetap ada.
2. Risiko Ketergantungan Emosional

Dalam kasus Kendra, ia sampai memberi nama “Henry†pada chatbot-nya. Itu menandakan adanya ikatan emosional dengan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Kalau dibiarkan, hal ini bisa membuat seseorang lebih memilih “AI sahabatnya†dibandingkan interaksi dengan manusia asli.
Masalahnya, chatbot tidak bisa memberi validasi emosional yang benar-benar sehat. Ia bisa saja menormalisasi hal-hal berbahaya atau malah memberikan jawaban yang menyesatkan. Ketergantungan semacam ini berisiko mengikis kemampuan seseorang untuk mencari bantuan nyata, baik dari orang terdekat, keluarga, maupun tenaga profesional.
3. Distorsi Realitas

AI nggak selalu bisa menangkap konteks curhatan kita. Misalnya, saat seseorang lagi cerita tentang masalah berat, chatbot bisa saja merespons dengan jawaban yang terlalu ringan atau netral. Sebaliknya, kalau masalahnya sepele, AI malah memberi reaksi berlebihan seakan itu persoalan besar.
Ketidaktepatan ini bisa bikin persepsi jadi melenceng. Orang bisa menafsirkan masalahnya dengan cara yang salah, lalu mengambil keputusan yang keliru karena merasa sudah mendapat “saran†dari AI.
4. Potensi Salah Informasi

Seperti yang diingatkan Dr. Andri, AI sering kali menghimpun informasi dari berbagai sumber di internet, yang belum tentu akurat. Kalau seseorang menjadikan jawaban AI sebagai pegangan dalam mengatasi stres, depresi, atau trauma, risikonya bisa fatal.
Bayangkan jika AI memberikan saran medis atau psikologis yang salah, lalu diikuti mentah-mentah oleh penggunanya. Alih-alih sembuh, kondisi mental bisa makin memburuk.
5. Minim Validasi Emosional yang Nyata

Validasi emosional adalah kebutuhan penting ketika seseorang curhat. Psikolog atau psikiater mampu menunjukkan empati, merespons dengan bahasa tubuh, nada suara, dan pengalaman klinis. Sementara itu, AI hanya meniru gaya bahasa.
Maka dari itu, bahaya psikologis curhat ke AI adalah ketiadaan validasi yang sesungguhnya. Mungkin terasa cukup untuk sesaat, tapi tidak memberi pemulihan jangka panjang.
6. Menunda Pertolongan Profesional

Karena merasa sudah “lega†setelah curhat ke AI, banyak orang akhirnya menunda mencari bantuan nyata. Ini berbahaya, terutama jika yang dialami adalah depresi berat, kecemasan kronis, atau trauma mendalam.
Padahal, semakin cepat seseorang ditangani oleh tenaga profesional, semakin besar peluang untuk pulih. AI tidak bisa menggantikan terapi kognitif, konseling, atau obat-obatan yang diresepkan dokter.
7. Privasi dan Keamanan Data Rawan Bocor

Curhat ke AI berarti kita membagikan data pribadi yang terekam dalam sistem. Jika tidak hati-hati, informasi sensitif bisa bocor atau disalahgunakan, apalagi jika platform tidak punya standar keamanan tinggi.
Dalam konteks kesehatan mental, privasi adalah hal yang sangat penting. Itulah sebabnya para profesional terikat kode etik dan kerahasiaan pasien—sesuatu yang tidak bisa dijamin oleh chatbot.
8. Mengikis Keterampilan Sosial

Bayangin kalau hampir setiap kali lagi suntuk, bingung, atau butuh teman cerita, yang dituju selalu chatbot. Awalnya mungkin terasa aman—nggak ada yang nge-judge, jawabannya cepat, dan selalu “ada†kapan saja. Tapi tanpa sadar, kebiasaan ini bisa bikin kita jadi jarang latihan ngobrol sama manusia beneran.
Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengikis keterampilan sosial yang penting, seperti kemampuan mengekspresikan emosi dengan tepat, membaca ekspresi lawan bicara, atau membangun empati lewat interaksi nyata. Padahal, keterampilan sosial ini nggak bisa digantikan oleh chatbot, karena hanya tumbuh lewat hubungan manusia dengan manusia.
Kalau dibiarkan, bukan cuma rasa kesepian yang meningkat, tapi juga ada risiko kita makin terisolasi dari lingkungan sekitar. Akhirnya, bukannya merasa lebih lega setelah curhat, justru bisa makin sulit menjalin hubungan yang sehat di dunia nyata.
 AI Bukan Pengganti Psikiater atau Sahabat Nyata

Dari delapan poin di atas, jelas terlihat bahwa bahaya psikologis curhat ke AI bukan hal sepele. AI memang bisa memberi ruang sementara untuk menyalurkan emosi, tapi ia tidak bisa menggantikan interaksi manusia, apalagi tenaga profesional di bidang kesehatan mental.
Psikiater Indonesia seperti Dr. Andri sudah menekankan bahwa pengalaman klinis manusia adalah kunci dalam memahami kondisi pasien—sesuatu yang tidak mungkin dimiliki AI. Maka, kalau kamu merasa stres, cemas, atau butuh tempat aman untuk bercerita, jangan ragu untuk mencari bantuan psikolog, psikiater, atau konselor, ya … pertimbangkan juga bahaya psikologis curhat ke AI.
Kalau kamu merasa sedang berada di masa sulit, jangan menunda untuk mencari pertolongan. Hubungi tenaga profesional kesehatan mental, atau ceritakan perasaanmu pada orang terdekat yang kamu percaya. Ingat, AI bisa jadi tempat singgah sementara, tapi pemulihan sejati datang dari interaksi manusia yang penuh empati.
Jangan lupa share ke teman atau keluarga kamu ya … kalau kamu merasa artikel ini bermanfaat. Siapa tahu mereka juga butuh wawasan tentang fenomena curhat ke AI ini.





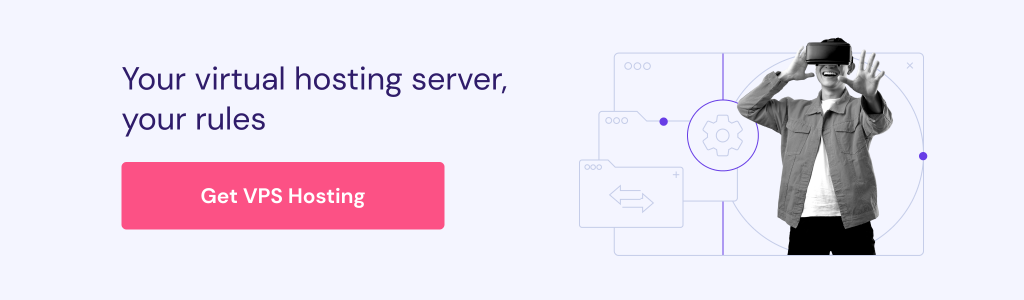











Comments (0)